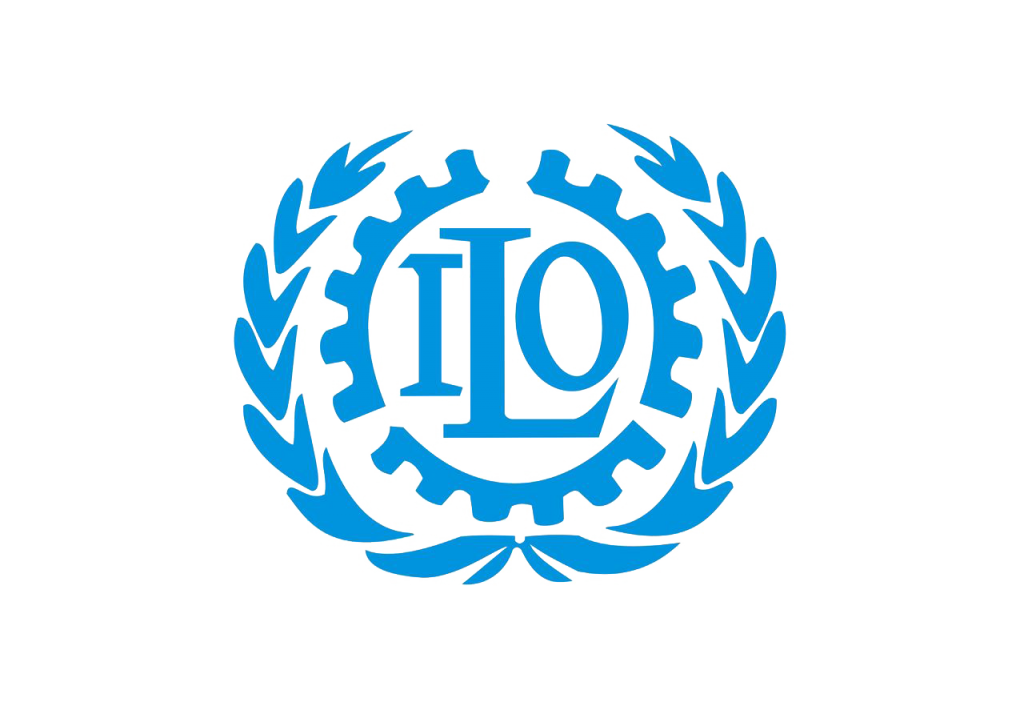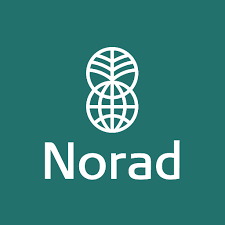Alamsya M. Dja'far*
Dalam Laporan Tahunan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) tahun 2017 yang dirilis Agustus 2018, Wahid Foundation (WF) mengajukan salah satu kesimpulan dan analisis berikut. Meningkatnya kasus-kasus pelanggaran seharusnya tidak dibaca jika masyarakat Indonesia sudah alergi dengan perbedaan agama atau keyakinan, melainkan salah satu bentuk keberhasilan praktik “politisasi agama”, penyalahgunaan simbol-simbol agama untuk bertarung dalam kontestasi politik di daerah maupun nasional.[1]
Laporan KBB WF merupakan laporan pemantauan dengan menggunakan metode berbasis peristiwa (event-based methodology), salah satu metode dalam pemantauan situasi hak asasi manusia (HAM). Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dicatat dan dihitung berdasarkan kategori pelanggaran dan praktik baik yang sudah ditetapkan. Data-data laporan diperoleh melalui beberapa antara pemberitaan media nasional, dan lokal, baik media cetak, elektronik maupun daring atau berdasarkan informasi yang diberikan jaringan lembaga dan ahli yang selama ini concern dalam isu-isu KBB, di tingkat nasional maupun lokal.
Sepanjang pilkada 2017 di Pulau Jawa, WF mencatat 28 peristiwa politisasi agama dengan 36 tindakan. Peristiwa paling banyak terjadi di DKI Jakarta (24 peristiwa) menjelang putaran pertama dan kedua. Jawa Barat (3 peristiwa) dan Banten (1 peristiwa) masing-masing menempati wilayah terbanyak kedua dan ketiga. korban individu terbanyak di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (10 tindakan), disusul Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Rano Karno di Banten. Laporan ini tidak menunjukkan politisasi agama berhasil di dua daerah lainnya.[2]
Salah satu masalah terbesar politisasi agama adalah karena bukan hanya menyasar individu, melainkan kelompok atau identitas tertentu. Dalam kasus Ahok, politisasi tidak menyasar Basuki “Ahok” semata, tetapi komunitas non-muslim dan Cina, identitas yang melekat pada Ahok. Bukan hanya pria kelahiran Belitung itu yang menjadi korban. Bahkan Anies Baswedan, pesaing Ahok, juga sebagai korban. Anies dituduh Syiah, komunitas muslim minoritas di Indonesia.
Seperti ditunjukkan banyak kasus konflik, praktik politisasi semacam ini juga menyasar kelompok paling rentan: perempuan dan anak selalu saja menjadi kelompok korban paling rentan. Pada putaran kedua pilkada Jakarta, beredar pesan ancaman ini di media sosial: “perempuan pendukung Ahok halal diperkosa”. Seorang nenek bernama Hindun ditolak disalatkan karena memilih Ahok. Seorang siswa SD di Jakarta Timur berinisial JSZ menjadi korban perisakan dengan menyebutnya “kafir” dan “Ahok”.[3]
Dalam banyak praktik politisasi kebencian semacam ini beberapa elemen penting yang harus menjadi tumpuan perhatian antara lain “pemanfaatan perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda” dan “usaha-usaha tertentu oleh para aktor”. Elemen yang pertama tak ubahnya “jerami bakar”. Dalam penelitian Cherian George, guru besar studi-studi media pada Departemen
Jurnalisme, Hong Kong Baptist University, fenomena yang disebutnya dengan “pelintiran Kebencian” semacam itu biasanya mengombinasikan dua hal: ujaran kebencian dan rekayasa ketersinggungan seperti yang pernah terjadi di masyarakat Buddha di Myanmar dan Kristen Ortodoks di Rusia.[4]
Merujuk Hasil Survei Tren Toleransi di Kalangan Muslim Perempuan tahun 2017, terdapat kecenderungan jika mayoritas responden muslim bersikap intoleran kepada kelompok yang tidak disukai. Sedikit dari mereka yang mau bersikap toleran. Survei yang dilakukan pada 6 – 27 Oktober 2017 di 34 provinsi tersebut menggunakan 1500 responden dengan teknik multi-stage random sampling dan margin of error ±2.6 persen.
Dalam survei, 57 % responden, setara 93.4 juta muslim Indonesia jika diproyeksikan ke dalam jumlah pemilih muslim yang sebanyak 164 juta orang, mengaku memiliki kelompok yang tak disukai. Sebanyak 57.1%, setara 53.3 juta dari 93.4 juta, bersikap intoleran.[5] Jumlah tersebut makin bertambah jika ditambah sebagian dari responden yang dikategorikan netral yang totalnya sebanyak 42.1%. Namun begitu, survei juga menunjukkan jika sebanyak 36% atau setara 56 juta muslim Indonesia mengaku tidak memiliki kelompok yang tidak disukai. Bisa dikatakan salah satu pekerjaan rumah mengurangi intoleransi adalah mengurangi kelompok yang tidak disukai. Sebab sikap dan perasaan memiliki kelompok yang tidak disukai pintu gerbang lahirnya intoleransi.
Dalam survei yang sama, terdapat sepuluh kelompok yang paling banyak tidak disukai responden muslim: komunis, LGBT, Yahudi, Kristen, Ateis, Syiah, Cina, Wahabi, Katolik, dan Budha. Kelompok-kelompok ini tidak jauh berbeda dengan survei WF setahun sebelumnya. Dalam survei WF, intoleransi ini disebut dengan “intoleransi umum” yang melihat kesediaan responden bersikap toleran kepada kelompok yang tidak disukai baik seagama maupun tidak.
Tentu saja ada banyak pengertian tentang toleransi. Pengertian yang longgar biasanya merujuk pada kesediaan untuk menerima perbedaan identitas (agama, jender, etnik, orientasi seks, afiliasi organisasi, dan lain-ain). Survei ini menggunakan konsep yang lebih dari sekedar menerima perbedaan, tetapi juga kesediaan memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak dasar warga negara dan tidak menghalangi atau melawan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Menurut John L. Sullivan, professor ilmu politik Amerika, perlawanan (opposition) dan ketidaksetujuan (disagreement) merupakan dua kata kunci memahami intoleransi, khususnya intoleransi politik.[6] Intoleransi dalam survei WF sendiri diukur lewat tiga ukuran apakah kelompok yang tidak disukai tersebut bisa menjadi tetangga, mengajar di sekolah negeri, atau menjadi pejabat pemerintah di negeri ini.
Dibanding dengan korban-korban pelanggaran KBB 2017, sepanjang empat tahun sebelumnya (2014-2017), terlihat dengan jelas bahwa korban terbanyak adalah mereka yang dianggap sesat, termasuk di dalamnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Gafatar. Dalam beberapa kasus, di wilayah-wilayah di mana jumlah dan relasi kekuasaan mereka minoritas, muslim bisa menjadi korban seperti kasus Masjid di Tolikara (Juli 2015) atau Masjid Syuhada di Sulawesi Utara (Nopember 2015).
Fenomena ini menunjukkan jika intoleransi bukan soal agama semata, tetapi tentang relasi kekuasaan (power relation) dan karenanya membutuhkan mekanisme perlindungan terhadap minoritas. Intoleransi juga menunjukkan fenomena “berbalas-balasan”. Berbekal data ini pula bisa disimpulkan penyesatan berbasis agama keyakinan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi isu intra dan antaragama di Indonesia. Penyesatan seringkali berakibat pada pelanggaran hak-hak dasar korban lainnya.
Jika dibandingkan sepanjang empat tahun terakhir, meski kasus-kasus pelanggaran meningkat, namun sebetulnya menunjukkan pola yang berubah: meninggalkan cara-cara kekerasan fisik. Jika pada 2004, “serangan fisik atau perusakan properti menjadi tindakan teratas pelanggaran oleh aktor non-negara (16 tindakan), tindakan ini tidak masuk di tiga tahun berikutnya. Pada 2017, paling banyak “ujaran kebencian” (35 tindakan) dan “intimidasi serta ancaman” (20 tindakan). Tampaknya dua tindakan pelanggaran ini masih akan dihadapi Indonesia setidaknya lima tahun mendatang.
Fenomena ini bukan khas Indonesia, Laporan Pew Research Center pada 2016 yang dirilis tahun 2018 menunjukkan negara-negara di Eropa (2.6) dan Amerika (skala 0.5) sepanjang periode mengalami peningkatan drastic dalam permusuhan sosial yang melibatkan agama. Sementara Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami penurunan meski tetap berada di paling atas dalam perbandingan wilayah. Pada umumnya korban permusuhan di negara-negara Eropa dan Amerika umat Islam. Selebihnya Yahudi. [7]
Karena praktik politisasi agama tidak selalu menunjukkan “watak” masyarakat, maka langkah strategis yang terus menerus dikembangkan adalah penguatan kohesi sosial dan solidaritas. Sebagai bangsa, Indonesia memiliki modal tersebut.
Dalam laporan KBB 2017, kasus-kasus pelanggaran memang meningkat. Tetapi, praktik-praktik baik juga meningkat sebagai respons atas kasus-kasus yang berkembang. Bentuknya rupa-rupa. Dari diskusi toleransi, pawai budaya, atau festival keagamaan yang melibatkan seluruh elemen bangsa pun digagas. Upaya ini terus meningkat dengan memanfaatkan momentum Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri di bulan Juni 2017. Dari masyarakat sipil, aktor terbanyak adalah komunitas lintas iman dan Gerakan Pemuda Ansor, sayap organisasi pemuda Nahdlatul Ulama.
Survei Nasional WF 2017 juga menunjukkan modal serupa. Di atas 80 persen responden muslim mengaku tak masalah hidup bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Hanya 10 persen yang merasa keberatan. Dukungan terhadap kebebasan menjalankan agama dan keyakinan menunjukkan angka mayoritas, 79 persen.
Tentu saja tantangan strategis lainnya adalah peran negara. Di dalamnya menyangkut peran pemerintah, legislatif, yudikatif, dan partai-partai politik. Performa peran Institusi-institusi tersebut amat menentukan wajah Indonesia di masa mendatang. []
Disampaikan dalam Seminar UKDW Yogyakarta, 6 Agustus 2017.
** Peneliti dan Program Manager Wahid Foundation Jakarta
[1] Wahid Foundation, “Mengikis Kebencian; Laporan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan 2017”, Agustus 2018. Dapat diunduh di sini http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Laporan-Tahunan-Kemerdekaan-BeragamaBerkeyakinan-KBB-di-Indonesia-2017
[2] Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota yang melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Di Pulau Jawa, daerah-daerah yang menggelar pilkada adalah provinsi DKI Jakarta dan Banten; Kabupaten Bekasi, Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap, Brebes, Kulonprogo; Kota Cimahi, Tasikmalaya, Salatiga, Yogyakarta, dan Batu. Lihat Wahid Foundation, “Mengikis Kebencian …,” 1.
[3] Wahid Foundation, “Mengikis Kebencian …,” 43.
[4] Cherian George, Pelintiran Kebencian, terj. (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017).
[5] Lihat Wahid Foundation, Laporan Survei Nasional “Tren Toleransi Sosial-Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia 2017, Januari 2018. Riset ini hasil kerjasama Wahid Foundation dengan Lembaga Survei Indoensia (LSI) dan UN Women. Hasil survei bisa diunduh di http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Laporan-Survei-Nasional-Tren-Toleransi-Sosial-Keagamaan-di-Kalangan-Perempuan-Muslim-di-Indonesia.
[6] John L. Sullivan, James E. Piereson, George E. Marcus, “An Alternative Conceptualization of Political Theory; Illusory Increases 1950s-1970,” The American Political Science Review, Volume 73, Issue 3 (Sept,1979), 784
[7] Pew Research Center, Global Uptick in Government Restriction on Religion 2016, 21 Juni 2018, 16
Bagikan Artikel: