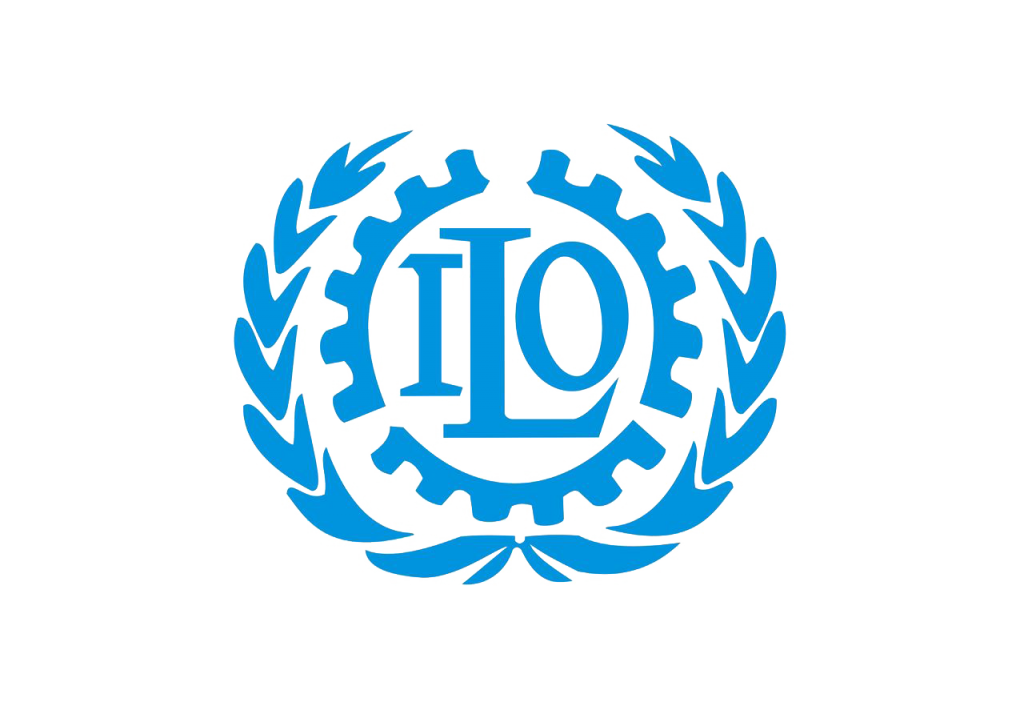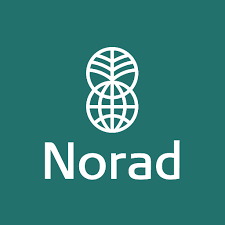Kembali
Kebebasan Beragama dalam Cengkeraman Digital: Regulasi dan Tantangan di Indonesia | Opini: Erti Fadhilah Putri
Ditulis : Admin
Rabu, 23 Oktober 2024

Kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak fundamental yang seharusnya dinikmati oleh setiap individu, termasuk di ruang digital. Namun, dalam penerapannya, hak-hak ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama ketika "diterjemahkan" dari konteks fisik ke dalam dunia digital.
Salah satu tantangan utama yang muncul adalah bagaimana menavigasi batas antara kebebasan berekspresi dengan ujaran kebencian, yang semakin marak terjadi di platform daring.
Platform media sosial kini menjadi alat bagi sebagian pihak untuk memobilisasi kebencian dan memicu tindak kekerasan. Misalnya, menyebarkan konten keagamaan yang salah atau bersifat hasutan yang menguntungkan kelompok tertentu.
Seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial, pelecehan, trolling, intimidasi, dan doxxing (pembocoran informasi pribadi tanpa izin) juga semakin meluas. Ancaman digital seperti ini tidak jarang berujung pada kekerasan fisik di dunia nyata.
Fenomena ini menjadi masalah serius di Indonesia, terutama karena tindakan keras pemerintah terhadap beberapa kelompok agama, serta penggunaan undang-undang penistaan agama untuk menargetkan kelompok minoritas agama.
Tantangan dan Ruang Digital
Internet dan platform media sosial telah menjadi medan pertempuran baru bagi kebebasan beragama dan berekspresi. Sayangnya, ruang digital di Indonesia semakin sering digunakan sebagai sarana untuk memobilisasi kebencian terhadap kelompok agama minoritas.
Beberapa platform daring, seperti Facebook, X (dulu Twitter), dan Instagram, menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian, pelecehan, trolling, dan ancaman terhadap kelompok rentan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) baru-baru ini merilis Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian Terhadap Kelompok Rentan dalam konteks Pemilu 2024. Laporan ini menunjukkan bahwa sekitar 13,82% dari 200 ribu teks yang dipantau mengandung ujaran kebencian, dengan Facebook diidentifikasi sebagai platform utama penyebaran konten negatif ini.
Temuan ini mencerminkan betapa seriusnya masalah ujaran kebencian di ruang digital, yang tidak hanya mengancam kelompok tertentu tetapi juga mengganggu kohesi sosial secara keseluruhan.
Salah satu isu yang mencolok dalam laporan tersebut adalah bagaimana topik-topik terkait agama, terutama yang melibatkan konflik global seperti serangan Israel-Palestina, memicu lonjakan ujaran kebencian terhadap berbagai kelompok.
Dalam konteks ini, kelompok-kelompok yang menjadi sasaran adalah Yahudi, penyandang disabilitas, serta minoritas agama, seperti Kristen, Syiah, dan Ahmadiyah.
Ujaran kebencian yang sering diarahkan kepada kelompok Ahmadiyah tercatat dalam laporan AJI, dengan contoh pernyataan yang sangat merugikan dan menyebarkan kebencian, seperti:
“Setelah Ahmadiyah (menggunakan agama Islam sebagai pemanis), kini mereka telah meng-upgrade diri, seperti ISIS yang mengobrak-abrik Islam, ternyata mereka pro-Israel. Seperti Ahmadiyah yang tidak berhasil mengobrak-abrik Islam. Apakah kiranya mereka tidak akan muncul dalam bentuk baru? Kami tahu mereka akan muncul dalam bentuk baru.”
Pernyataan ini jelas mencerminkan bagaimana kebencian terhadap Ahmadiyah tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga menciptakan stigma dan diskriminasi yang lebih luas.
Selain itu, dalam laporan Wahid Foundation: Satu dekade Ujaran Kebencian juga mencatat bahwa beberapa ujaran kebencian diarahkan kepada umat Nasrani, khususnya terkait dengan sorotan yang muncul akibat konflik pendirian rumah ibadah mereka. Ketegangan semacam ini dapat memperburuk keadaan dan meningkatkan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok minoritas dalam masyarakat.
Penting untuk menyikapi temuan ini dengan serius, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian terhadap keberagaman dan toleransi di Indonesia. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyebaran ujaran kebencian dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan menjadi langkah-langkah yang krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.
Kerangka Hukum di Indonesia: UU ITE dan Pasal Penodaan Agama
Salah satu hambatan besar terhadap kebebasan beragama di ruang digital adalah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Penodaan Agama. UU ITE, yang awalnya dirancang untuk mengatur transaksi elektronik dan mencegah penyalahgunaan teknologi informasi, telah berkembang menjadi instrumen untuk menindak ujaran kebencian, namun sayangnya sering kali digunakan untuk menargetkan ekspresi keyakinan yang berbeda atau dianggap menyimpang.
Pasal 28 Ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meskipun niatnya baik untuk melawan ujaran kebencian, penegakannya sering kali selektif dan condong menargetkan kelompok minoritas agama. Misalnya, penggunaan UU ITE terhadap kasus penistaan agama banyak terjadi pada kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran resmi negara, seperti Ahmadiyah dan Syiah.
Undang-Undang Penodaan Agama, yang diperkenalkan pada tahun 1965, juga sering digunakan untuk menghukum ekspresi keyakinan yang tidak sesuai dengan enam agama yang diakui oleh negara (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu).
Meskipun selama empat dekade pertama hanya ada delapan kasus yang diajukan berdasarkan undang-undang ini, angka tersebut terus meningkat secara signifikan, khususnya sejak era Reformasi.
Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah hukuman terhadap Lina Lutfiawati, seorang influencer media sosial yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda $16.000 karena penistaan agama setelah mengunggah video di mana ia mengucapkan doa Islam sebelum mengonsumsi babi.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana undang-undang penistaan agama digunakan untuk mengontrol ekspresi pribadi di ruang digital dan sering kali digunakan dengan cara yang merugikan minoritas.
Regulasi Baru: KUHP dan Smart Pakem
Pada awal 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku pada 2026. KUHP ini mengkriminalisasi lebih lanjut tindakan penistaan agama dan memperluas cakupan pengaturan kebebasan beragama, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis hak asasi manusia.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga menggunakan teknologi seperti aplikasi Smart Pakem untuk melacak dan melaporkan keyakinan yang dianggap menyimpang. Meskipun aplikasi ini sekarang tidak lagi tersedia di Google Play Store, dampaknya sudah terasa, terutama terhadap komunitas-komunitas kecil seperti Ahmadiyah, yang semakin terisolasi dan termarjinalisasi.
Tantangan terhadap Hukum Internasional
Pengaturan kebebasan berekspresi dan beragama di Indonesia juga menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 18 dan 19 ICCPR menjamin kebebasan beragama serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Meskipun kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak asasi manusia lainnya, pembatasan ini harus memenuhi prinsip-prinsip hukum internasional, yaitu harus proporsional, berdasarkan hukum, dan diperlukan untuk tujuan yang sah, seperti melindungi ketertiban umum atau hak-hak orang lain.
Sayangnya, dalam banyak kasus di Indonesia, pembatasan yang diberlakukan melalui UU ITE dan undang-undang penodaan agama tidak selalu sejalan dengan standar internasional tersebut. Alih-alih melindungi minoritas, regulasi ini sering digunakan sebagai alat represi untuk menekan kelompok yang tidak sejalan dengan pandangan mayoritas atau pemerintah.
Rekomendasi
Rekomendasi untuk penanganan ujaran kebencian di Indonesia mencakup dua langkah penting. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur penanganan ujaran kebencian, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Penambahan norma diperlukan untuk memperjelas definisi dan unsur-unsur ujaran kebencian yang sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Kepolisian juga harus merevisi Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian dengan menghapus Pasal 310, 311, dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pemidanaan ujaran kebencian, dan sangat disarankan untuk menghapus Pasal 156a KUHP guna menangani kasus penodaan.
Revisi surat edaran ini juga harus mencakup pencantuman prinsip-prinsip pemidanaan yang merujuk pada Rabat Plan of Action, serta pengkategorian ujaran kebencian menjadi tiga tingkat (ringan, sedang, dan berat) sesuai rekomendasi dari Article 19, sehingga kepolisian dapat lebih fokus pada kasus yang lebih serius, sementara kasus ringan dapat diselesaikan melalui pendekatan sosial.
Kedua, penting untuk meningkatkan kapasitas aparat kepolisian dan kejaksaan melalui pelatihan dan forum pertukaran pengetahuan terkait pemidanaan kasus ujaran kebencian, dengan harapan langkah-langkah pemidanaan tersebut sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip HAM.
Referensi
Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (2024). Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian Terhadap Kelompok Rentan pada Pemilu 2024. Diakses dari https://aji.or.id/system/files/2024-08/laporan-pemantauan-ujaran-kebencian-terhadap-kelompok-rentan-pada-pemilu-2024bahasa-indonesia.pdf.
Tirto.id. (2019, Januari 11). Aplikasi Smart Pakem dan Tren Memburuknya Kebebasan Beragama. Tirto.id. Diakses dari https://tirto.id/aplikasi-smart-pakem-dan-tren-memburuknya-kebebasan-beragama-davP.
U.S. Department of State. (2023). 2023 Report on International Religious Freedom: Indonesia. Diakses dari https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/indonesia/.
Bagikan Artikel: